Marhaban Ya Ramadhan. Dari Cahaya Spiritualitas ke Pragmatisme
Reporter : Redaksi

Sejak fajar peradaban, agama lahir sebagai nyala kecil di hati manusia—api yang memberi terang dalam gulita eksistensi. Ia bukan sekadar sistem aturan, melainkan denyut batin yang membimbing manusia memahami misteri keberadaan.
Namun, sebagaimana aliran sungai yang melewati zaman, agama tak luput dari perubahan. Dari sebuah oase spiritualitas, ia perlahan membentuk saluran-saluran institusional, hingga akhirnya berubah menjadi samudra luas yang diwarnai kepentingan dan kekuasaan.
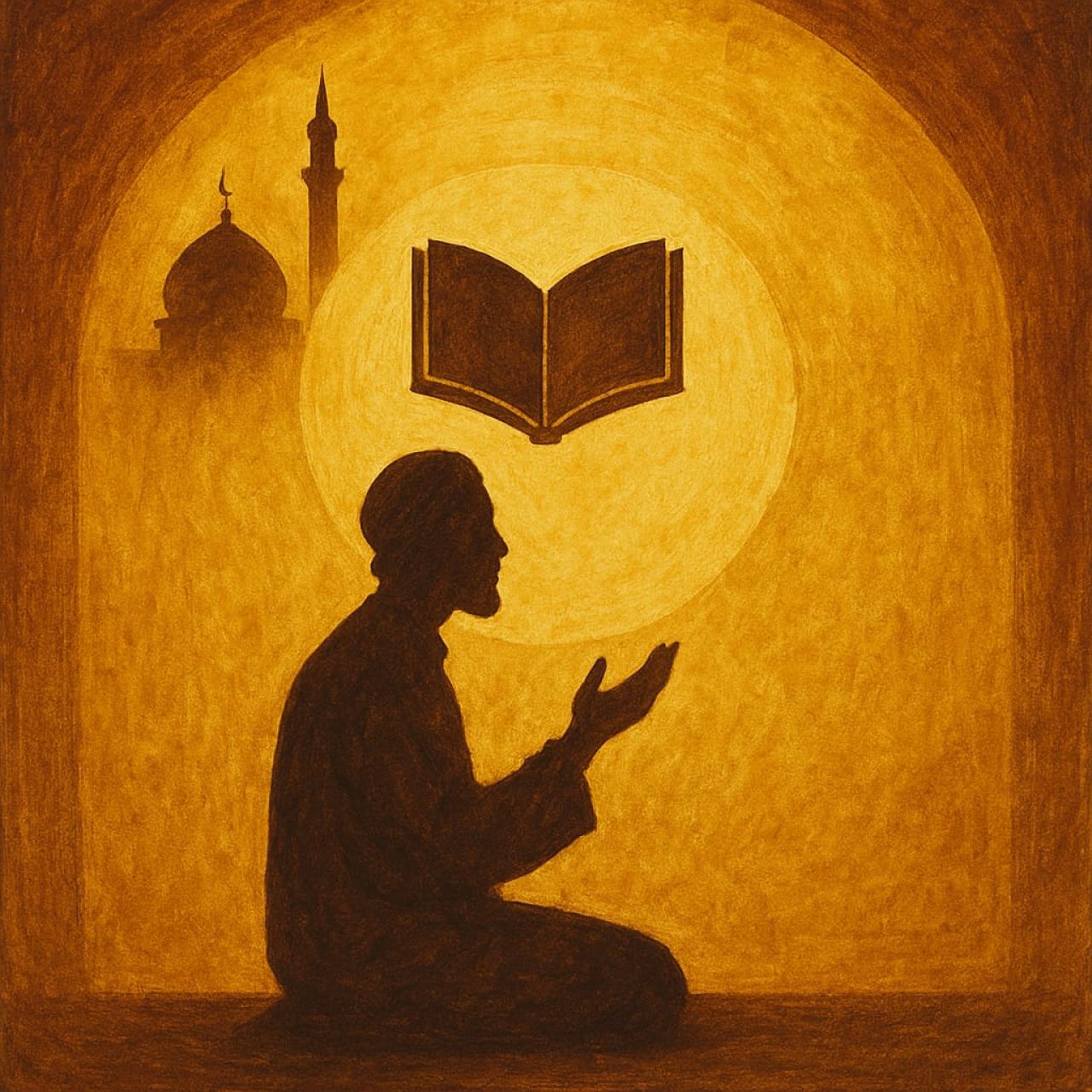
Dari gua pertapaan hingga mimbar-mimbar megah, dari kesederhanaan pencarian makna hingga kompleksitas birokrasi dogmatis, agama telah bermetamorfosis.
Ia bukan lagi sekadar jalan sunyi menuju pencerahan, melainkan juga panggung bagi mereka yang mengejar eksistensi sosial, pengaruh, bahkan keuntungan duniawi.
Agama Adalah Cahaya
Sejarah spiritualitas manusia bermula dari bisikan-bisikan hati yang merindukan makna. Dalam keheningan padang pasir, di balik rerimbunan hutan suci, manusia mendengar suara Tuhan dalam berbagai manifestasi.
Mircea Eliade, sejarawan agama ternama, menyebut fase ini sebagai “hierophany”—momen ketika sesuatu yang biasa berubah menjadi sakral.
Dalam setiap ritual, doa, dan pengorbanan, manusia tidak sekadar beribadah, tetapi juga berdialog dengan yang transenden.
Agama pada tahap ini adalah cermin jernih yang memantulkan pencarian manusia akan makna.
Seperti benih yang tumbuh di tanah subur, ia hadir untuk memberi kehidupan, menguatkan moralitas, dan membimbing manusia menuju kebijaksanaan.
Namun, agama perlahan beranjak dari spiritualitas murni menuju ranah yang lebih kompleks—hierarki, institusi, dan aturan yang semakin membingkai serta membatasi esensinya.
Ketika Cahaya Menjadi Lembayung
Ketika manusia mulai membangun tempat beribadah dan mendirikan aturan sakral, agama memasuki fase institusional. Hierarki keagamaan muncul, membawa serta struktur kepemimpinan yang menafsirkan doktrin dan mengatur praktik ibadah.
Pada titik ini, agama tak lagi hanya tentang hubungan individu dengan yang Ilahi, tetapi juga menjadi sistem sosial yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Filosof Karl Marx melihat fenomena ini sebagai bentuk “alat kontrol sosial”, di mana agama sering kali digunakan oleh elite untuk menjaga status quo.
Dalam perkembangan sejarah, agama kerap berjalan beriringan dengan kekuasaan duniawi.
Para pemuka agama bernegosiasi dengan penguasa, membentuk aliansi yang tak selalu selaras dengan nilai-nilai spiritual awal. Ritual dan doktrin mulai menjadi alat legitimasi, bukan sekadar sarana pencerahan.
Agama yang dulunya adalah pelita kini menjadi mercusuar megah, namun di balik cahayanya, bayang-bayang kepentingan mulai tampak.
Retaknya Cermin Spiritual
Ketika agama memasuki ranah pragmatisme, perpecahan menjadi tak terelakkan. Kelompok-kelompok kecil bermunculan, masing-masing membawa tafsir dan agenda sendiri.
Perbedaan ideologis yang seharusnya menjadi mozaik keindahan berubah menjadi jurang pemisah.
Max Weber, sosiolog klasik, menjelaskan fenomena ini sebagai “disenchantment of the world”
ketika agama, yang semula penuh magi dan spiritualitas, semakin rasional dan birokratis. Dalam dunia yang semakin modern, agama tak hanya menjadi pegangan spiritual, tetapi juga alat tawar-menawar politik, ekonomi, bahkan kekuasaan.
Di titik ini, muncul fenomena yang bisa disebut “pelacuran spiritual”—ketika nilai-nilai agama dikorbankan demi keuntungan duniawi.
Agama dijajakan di mimbar-mimbar kekuasaan, disulap menjadi komoditas politik, atau menjadi alat mobilisasi massa demi kepentingan sesaat.
Bayang-bayang pragmatisme telah menodai cermin spiritualitas.
Mencari Cahaya Hilang

Namun, tidak semua penganut agama terjebak dalam arus ini. Masih ada mereka yang setia pada esensi spiritualitas, yang melihat agama bukan sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai jalan sunyi menuju kebenaran.
Tantangan terbesar bagi masyarakat modern adalah bagaimana menyeimbangkan antara struktur institusional agama dengan nilai-nilai spiritual fundamentalnya.
Jika agama ingin tetap relevan tanpa kehilangan kesuciannya, maka ia harus kembali pada akar pencariannya: sebuah perjalanan batin menuju makna, bukan sekadar instrumen sosial yang kehilangan rohnya.
Seperti fajar yang selalu datang setelah gelap, selalu ada harapan bahwa agama dapat kembali menjadi cahaya bukan sekadar alat pragmatisme, melainkan lentera yang membimbing manusia menuju kebijaksanaan sejati.
Penulis : Bambang Eko Mei
Pemerhati Sosial
Kanal Kolom adalah halaman khusus layanan bagi masyarakat untuk menulis berita lepas.
Redaksi Jatimkini.com tidak bertanggungjawab atas tulisan tersebut
Editor : Redaksi
e-Magazine











Berita Tebaru





Trending Minggu Ini






