Sayang, Umat Tidak Meniru Nabi Muhammad Dalam Mengajar Agama
Reporter : Rokimdakas

JATIMKINI.COM, Salah satu tujuan hidup manusia di dunia adalah mewariskan informasi dan pengetauan yang bermanfaat yang kita pelajari selama hidup di dunia kepada generasi berikutnya. Dari kutipan inilah perbincangan saya, Rokimdakas (RD) dengan Mas Tjuk Suwarsono (TS) guru jurnalistik ketika bekerja di Harian Sore Surabaya Post via WhatsApp berlangsung.
Kali ini temanya mengkritisi pola pengajaran agama Islam yang tidak berkiblat pada tata cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dominan syareat, yang sebetulnya diperuntukkan bagi kalangan anak dan remaja. Sedangkan untuk yang berumur fase ajarannya hakekat. Berikut kutipan dialognya, semoga bermanfaat.
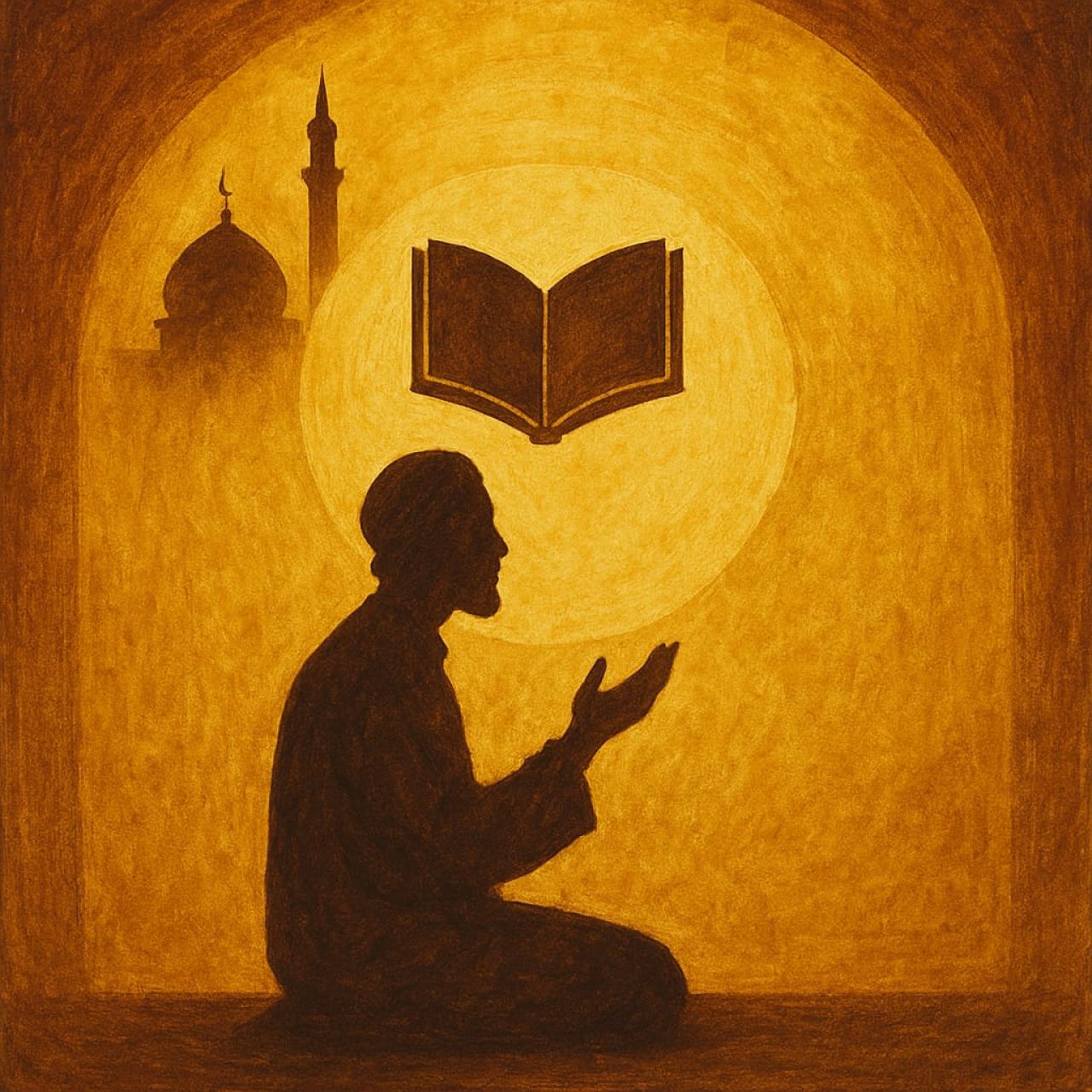
RD: Mas, dialog kita berangkat dari puisi saya ya? Ini kutipan bait terakhir " Tuhan, jika Engkau benar ada,mengapa tikus-tikus itu tak Kau beri azab? Atau mungkin mereka lebih pandai berdoa daripada kami yang sekadar meminta keadilan? Jika keadilan hanya dongeng usang maka biarlah kami menciptakan Tuhan baru. Tuhan yang peduli pada derita kami. Bukan Tuhan yang membiarkan kami bertanya tanpa pernah mendapat jawaban "
TS: Dik, kalau begini terus, anak-anak muda kita bisa kehilangan arah. Mereka mulai mencari "Tuhan Baru" sesuai persepsi masing-masing yang sering kali kosong makna. Kalau moralitas mereka terus merosot negara ini bisa benar-benar bangkrut.
RD: Mas, sejak dulu orang tua kita juga sudah khawatir soal moralitas bangsa. Tapi toh kita masih bertahan. Selama budi pekerti dan sopan santun dijaga keadaan bisa lebih aman. Soal ketuhanan, itu perjalanan pribadi setiap orang. Pemahaman dan penghayatan akan menemukan jalannya sendiri. Agama sering kali lebih menjadi bagian dari budaya. Ritual pernikahan, kematian, dan ibadah formal lainnya adalah bentuk budaya, bukan wahyu langsung dari langit.
TS: Setuju. Budaya paling dasar itu sopan santun dan budi pekerti, semisal "mikul dhuwur mendhem jero". Tapi, kalau anak-anak sekarang sudah kehilangan itu bagaimana jadinya?
RD: Semuanya kembali ke pola pendidikan di rumah. Ibu adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya. Lingkungan dan teman juga ikut membentuk karakter.
TS: Masalahnya, sekarang anak-anak belajar lebih banyak dari media sosial. Bahkan di pelosok desa pun virus budaya buruk sudah menyebar.
RD: Itu memang tantangan zaman. Tapi setiap fenomena punya mekanisme seleksi alami. Yang baik akan bertahan dan menjadi contoh bagi yang lain.
TS: Sepertinya kita butuh kerja sama besar, total football. Kalau dibiarkan berjalan parsial maka hasilnya tidak maksimal.
RD: Ibarat benang kusut, sulit mencari ujungnya. Karena itu setiap solusi yang diambil tampak parsial. Tapi tetap harus ada upaya dan prasangka baik bahwa masalah pasti akan menemukan jalannya sendiri untuk terurai.
TS: Tapi ada masalah besar di sini. Kita menghadapi "Moral Hazard" yang akut. Kebiasaan menyimpang sudah dianggap wajar dalam masyarakat. Ini diwariskan turun-temurun dan sudah menjadi budaya yang menyimpang. Ironisnya, pendidikan tinggi, tradisi luhur, bahkan agama pun tidak mampu mencegahnya. Kita sering meremehkan bangsa lain yang dianggap kurang religius tetapi moral mereka justru lebih baik daripada kita.
RD: Mungkin kita sedang membayar karma dari kesalahan pola ajaran agama yang tidak berakar pada budaya kita sendiri.
TS: Maksudmu, karena kita mengadopsi agama dari luar?
RD: Iya, terutama Islam.
TS: Hehe... makanya kita ini bermental importir bukan produsen.
RD: Yang jadi masalah bukan pada ajarannya tapi cara kita mempelajari. Mari kita lihat bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan Islam. Dalam 23 tahun, beliau berhasil mengubah masyarakat jahiliyah menjadi beradab. Tapi apa yang dia lakukan di awal? Selama 13 tahun pertama di Mekah, beliau tidak langsung mengajarkan syariat. Beliau lebih dulu mengajarkan kesadaran ketuhanan (tarekat). Mengajarkan manusia untuk mengenal Tuhan sebelum ada perintah ibadah.

Baru setelah mereka mengenal Tuhan dengan benar, mereka mencapai waskita (makrifat). Ada kesadaran bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam diri mereka. Di fase ini, mereka tidak butuh perintah khusus untuk berbuat baik. Mereka otomatis berperilaku sesuai sifat Tuhan yang mencintai kebaikan dan menjauhi keburukan. Setelah komunitas yang "menuhan" ini terbentuk barulah lahir syariat. Jadi, syariat itu bukan aturan yang ditegakkan dulu melainkan hasil dari kesadaran spiritual yang sudah matang yang membentuk perilaku.
TS: Wah, menarik ini. Berarti syariat itu lebih seperti efek samping dari karakter yang sudah baik, bukan aturan yang harus dipaksakan?
RD: Tepatnya begitu. Tapi setelah Nabi wafat, pola ajaran ini berubah. Di masa khalifah, Islam dikelola sebagai politik kekuasaan bukan lagi sebagai pembentukan kesadaran spiritual. Aturan-aturan syariat yang baru justru dirumuskan dua atau tiga abad setelah Nabi wafat, setelah adanya kertas dari Cina yang memungkinkan ilmu fiqih ditulis dan dikodifikasi.
Sejak saat itu, ajaran Islam lebih banyak berfokus pada hukum syariat, bukan lagi pada pencapaian spiritual personal. Beragama tapi tidak memiliki kesadaran bertuhan. Bertuhan tapi tidak beradab. Itu karena sifat beragamanya tekstual, bukan esensial.
TS: Makanya banyak orang sekarang yang beragama tapi kehilangan esensinya. Mereka sibuk menjalankan aturan tapi hati dan pikirannya kosong.
RD: Nah itu dia. Karena itulah kita punya banyak orang yang saleh dalam ritual tapi tidak dalam perilaku. Mereka beribadah rajin tapi tetap korup, tetap menipu, tetap memperdagangkan agama. Padahal kalau kita melihat sejarah lebih dalam, konsep "Tuhan" sendiri adalah konstruksi budaya manusia. Sebutan Tuhan baru muncul sekitar 70.000 tahun lalu ketika bahasa manusia mulai berkembang. Sejak saat itu manusia mulai merumuskan konsep agama sesuai zamannya.
TS: Jadi menurutmu tidak ada yang namanya "agama langit"?
RD: Semua agama diciptakan manusia di bumi. Setiap agama adalah hasil dari peradaban yang sedang berkembang saat itu. Makanya saya sering bilang kepada teman-teman yang masih gelisah soal keimanan, "Sing tatag ae". Yang penting tetap berbuat baik dan hidup beradab.
Perkara setelah mati, biarkan orang yang masih hidup yang mengurusnya. Setelah mati, fase kemanusiaan kita selesai. Tidak ada yang bisa membuktikan apa pun soal surga, neraka atau siksa kubur. Semua itu hanya konsep dalam teks agama yang tidak memiliki bukti nyata.

TS: Jadi menurutmu keyakinan tentang kehidupan setelah mati itu hanya fantasi spiritual?
RD: Memang. Keyakinan sejati harus berlandaskan kenyataan bukan fiksi atau dogma yang tidak bisa dibuktikan. Jika seseorang hanya percaya pada sesuatu yang tidak nyata bukankah itu sama saja dengan mempercayai fiksi?
TS: Pesan utama dari dialog ini apa?
RD: Pola ajaran agama yang ada saat ini cenderung berfokus pada aturan dan hukum bukan pada kesadaran spiritual. Jika kita ingin mengembalikan esensi agama maka kita harus menghidupkan kembali ajaran tentang kesadaran ketuhanan, bukan hanya sibuk dengan ritual yang kehilangan makna.
Yang lebih penting dari sekadar menjalankan aturan adalah menjadi manusia yang beradab. Sebab pada akhirnya, agama yang paling tinggi adalah agama kemanusiaan.
Editor : Ali Topan
e-Magazine











Berita Tebaru





Trending Minggu Ini





